Retret Dalam Biara Kemiskinan Rakyat
- account_circle Penulis
- calendar_month Sen, 29 Sep 2025
- visibility 209
- comment 2 komentar

![]()
Oleh : Marsel Robot, Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana
Ketika rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) sempoyongan memikul beban kemiskinan sekujur hidupnya sembari diancam oleh pertanyaan paling primitif: “apa hari ini ada makan?” Gubernur Lakalena dan ratusan hulubalangnya malah ugal-ugalan menghabiskan uang 1.6 miliar rupiah dengan menyemburkan diksi begitu suci, retret.
Padahal, beberapa hari sebelumnya ia menghabiskan puluhan miliar dirogo (baca diambil, red) dari brankas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai Tour De Entente. Entah kekeliruan, tetapi ini keterlaluan. Atau sebut saja kedurjanaan etis.
Padahal, retret merupakan ruang di mana sekelompok orang melakukan perjalanan ke dalam diri sambil menengadah memandang dan mengundang Yang di Atas. Lalu, menggunting koneksitas dengan rutinitas keseharian yang teramat profan, dan masuk ke ruang khusuk, berumah dalam kesunyian untuk menikmati Sang Sunyi.
Saya mengandaikan retret dilakukan dalam biara kemiskinan rakyat. Sebab, retret yang dilakukan para pejabat masuk dalam ruang kemewahan, di ruang full air conditioning (AC) dengan meja makan penuh menu premium. Karena itu, bagi saya, retret yang dilakukan oleh pejabat Provinsi NTT adalah bentuk penistaan terhadap rakyatnya.
Jikalau Anda dengan komplotan atau para berhala jabatan itu ingin melakukan ret-ret untuk membaca keadaan rakyat atau sekejap menikmati penderitaan rakyat, maka guntinglah rutinitas kantoran yang gitu-gituan. Lalu, pergilah menuju rumah reot rakyatmu, dan lihatlah penampakan mereka; bagaimana lakon melodramatik kehidupan mereka yang bernaung di bawah rindang pertanyaan: apa bisa makan hari ini? Retret kerakyatan ialah perjalanan batin menuju ke dalam biara kemiskinan rakyat bersemadi di kolong rumah mereka yang reot ditimpa nasib peot itu.
Kaum rohaniwan bertitah, retret, adalah seni berjalan ke dalam diri sendiri biar lebih intensif berdialog dengan Ilahi. Namun, para pejabat melakukan perjalanan “ke dalam” lobi hotel” sambil memutuskan koneksi dari dunia profan bukan dengan kesadaran asketis, melainkan dengan hasrat hedon. Mereka menutup akun publik. Lalu, masuk ke akun pribadi dengan password “biarkan kami bahagia tanpa dirimu”.
Rakyat di luar sana masih terseok mencoba membelokkan angin nasib sembari menggendong anaknya dengan pertanyaan yang tergantung di lehernya, adakah nasi di atas piring nasib yang kian rabun. Sementara para pejabat sibuk memilih tipe kasur: spring bed atau full latex? Lalu, mereka menundukkan kepala bukan berdoa, melainkan karena sedang menutup mata agar tidak melihat angka 1.6 miliar rupiah yang melayang seperti malaikat pemberat dosa.
Barulah saya paham, rupanya retret telah diperluas maknanya menjadi perjalanan ke dalam lobi hotel sambil karaoke dan coffee break. Di sana tak ada gua yang berlumuran sunyi seperti milik para rohaniwan, yang ada hanya ruang meeting dengan backdrop bertuliskan “Merefleksi Diri Menuju Pemerintahan Bermartabat”, walaupun yang direfleksikan adalah wajah sendiri yang tampak lebih bersinar karena terkena lampu kampus Universitas Pertahanan (Unhan).
Saya tiba-tiba membayangkan, seandainya Friedrich Nietzsche hidup hari ini dan ikut retret ke Unhan (Belu), saya yakin, ia pasti lebih memilih pensiun dini dari filsuf. Segera ia banting setir menjadi vendor retret spiritual, karena Tuhan telah mati. Sehingga, tidak perlu repot-repot lagi menanyakan “apa itu pengabdian dan kebaikan?” ‘ Cukup siapkan konsumsi prasmanan dan simfoni di beranda Unhan.
Jikalau jujur sejenak: retret bukanlah laku meninggalkan keriuhan dunia profan, melainkan seni mengganti suasana yang diongkos oleh rakyat. Yang dihapus bukan dosa, melainkan rasa bosan rutinitas kantor. Yang dilantunkan bukan lagu rohani, melainkan lagu Pance Pondaag, “Untuk Sebuah Nama”.
Sebetulnya, saya ingin ajukan satu usul kecil dari pinggir kiri sejarah; retret berikutnya janganlah di hotel atau di Unhan. Lakukanlah retret di rumah warga miskin di Lamaknen (Belu), di Molo (Soe), di Aplal (TTU) yang lantai rumahnya masih tanah, peninggalan Sang Pencipta dan atapnya masih meminjam langit. Jangan siapkan konsumsi mewah, cukup duduk di dapur sambil mendengarkan alunan saxofon dari periuk kosong dan dentingan bunyi jazz dari sendok-sendok di atas piring kosong.
Dan doa paling jujur bukan dilantunkan di aula ber-AC, melainkan di tengah panas yang tidak bisa kau stel dengan remote. Renungan paling benar bukan lahir dari kertas-kertas ceramah, melainkan dari tatapan seorang ibu yang berkata dengan tubuhnya: “Tuan-tuan, kapan engkau menikmati lapar bersamaku?”
Rakyat NTT telah lama hidup dalam kemiskinan, tempat penderitaan diterima sebagai takdir. Hampir tak cukup persediaan logika di cakrawala kesadaran untuk menalarkan keadaan itu. Kecuali, kepasrahan yang begitu mesra : Nanti Tuhan Tolong (NTT). Freire menyebut fenomena ini sebagai kebudayaan bisu — sebuah kondisi ketika rakyat hanya diberikan bahasa doa, tetapi tidak diberikan bahasa kritis untuk menggugat struktur yang menindas. Retorika religius yang pasif, dengan demikian, berfungsi sebagai “biara ideologis” tempat rakyat diam, sementara penguasa semakin bebas merayakan pesta.
Dalam tatapan Erich Fromm, keadaan ini disebut sebagai alienasi: keterasingan manusia dari makna hidupnya. Rakyat yang lapar, yang setiap hari dihadapkan pada pertanyaan sederhana — “Apakah hari ini ada makan?” — sesungguhnya tengah hidup dalam alienasi ganda. Pertama, mereka terasing dari kebutuhan dasarnya karena temperamen pejabatnya. Kedua, mereka terasing dari makna religius karena agama dijadikan tameng ideologis penguasa. Dalam kosa kata Albert Camus, inilah absurditas: penguasa merayakan hidup dengan pesta, sementara rakyat bertahan hidup dengan pasrah dan doa dengan seribu lilin di alaman kantor untuk melegasi korupsi sebagai “berkat”.
Inilah kuasa simbolik pejabat-pejabat kita: diksi suci dijadikan spanduk untuk menutup borok keserakahan. Mereka menyebutnya retret, padahal sebetulnya hanya liburan dibayar rakyat. Mereka bilang perjalanan koordinasi, tapi yang berjalan justru saldo APBD untuk menu premium di meja makan.
Seorang pemimpin yang sungguh-sungguh ingin merenung tidak membutuhkan anggaran miliaran; ia hanya butuh cukup keberanian untuk duduk di rumah warga miskin, menyentuh tangan mereka yang retak oleh tova dan kapak, dan mendengar detak lapar di wajah yang mereka sembunyikan dengan senyum. Di situlah retret paling jujur dimulai. Bukan dari aula megah dengan lampu sorot menguatkan hasrat hedonistik, melainkan dari gua-gua realitas yang sepat, amis, dan getir.(*)
- Penulis: Penulis






















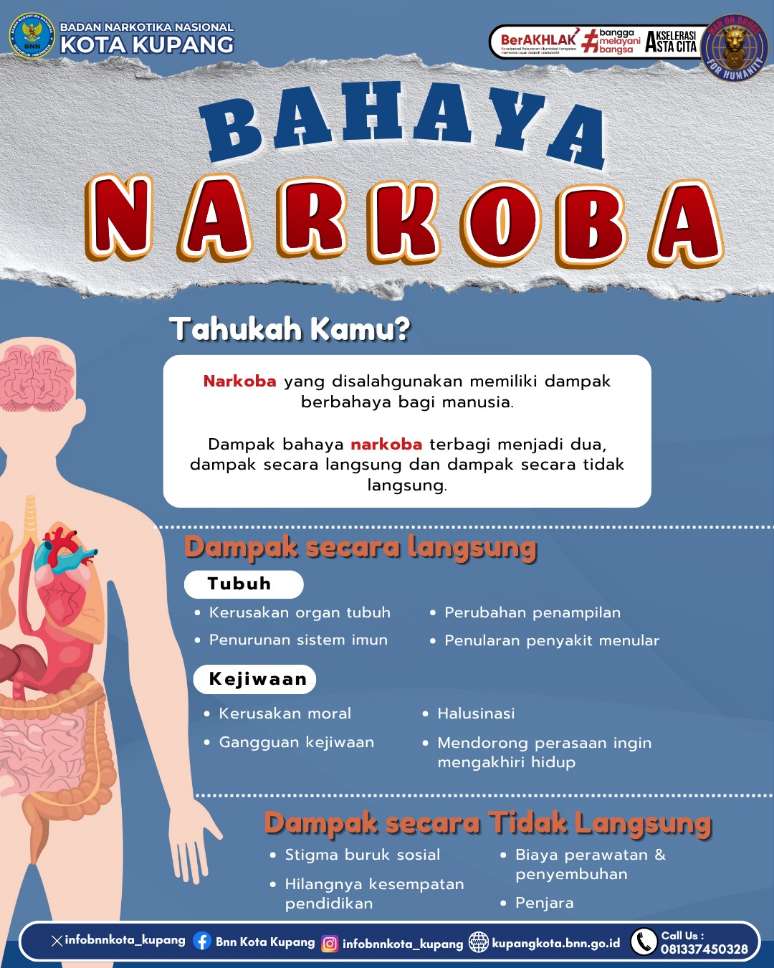






Setuju sekali dengan pikiran cerdik, tuntas, kritis dan iklas dari Bp Dr. Marcel Robot. Semoga ada pejabat yang menyimak dan meresapi pesan dalam buah pikiran ini.
30 September 2025 12:49 pmParadoks gaya pejabat dan rakyat papah. Harus diberi pelajaran pada gaya yang demikian.
30 September 2025 7:52 am