Nalar Diserahkan Hidup Ikut Diatur
- account_circle Penulis
- calendar_month 5 jam yang lalu
- visibility 84
- comment 0 komentar

![]()
Di banyak tempat, orang menjalani hari dengan pola yang nyaris sama. Bangun, bekerja, memenuhi kewajiban, lalu mengulanginya esok hari. Di sela-sela itu, muncul keluhan tentang aturan, sistem, atau orang-orang yang “berkuasa”. Anehnya, keluhan sering berhenti di sana. Jarang berlanjut menjadi pertanyaan yang lebih dalam: mengapa kita begitu mudah menerima, bahkan ketika merasa tidak sepakat?
Sebuah survei yang dirangkum dalam laporan OECD tentang literasi orang dewasa menunjukkan bahwa banyak pembaca berhenti membaca buku serius setelah usia sekolah, bukan karena tak mampu, tetapi karena merasa tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Buku-buku pemikiran dianggap berat, padahal di sanalah latihan bernalar dilakukan. Dalam bahasa sederhana, nalar jarang dipakai bukan karena rusak, melainkan karena jarang diajak bekerja. Inilah masalah utama yang sejak lama disoroti William Godwin: ketika akal sehat tidak dilatih, manusia cenderung menyerahkan hidupnya pada kebiasaan dan otoritas.
Pelan-pelan saja. Tidak ada tuntutan untuk menjadi berbeda secara drastis. Yang penting adalah memahami beberapa gagasan dasar yang bisa membantu menata ulang cara memandang diri dan dunia.
Menyadari hak bernalar
Godwin percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan bernalar yang setara. Masalahnya bukan pada kecerdasan, tetapi pada keberanian menggunakan nalar itu. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa urusan besar adalah urusan mereka yang “lebih tahu”. Akibatnya, kebiasaan berpikir mandiri jarang dipakai, seperti otot yang lama tidak digerakkan.
Pada kehidupan sehari-hari, ini tampak sederhana. Ketika mendengar aturan baru di tempat kerja, banyak yang langsung patuh tanpa bertanya tujuan atau dampaknya. Bukan karena setuju, tetapi karena merasa bertanya hanya akan menambah masalah. Padahal, bertanya bukan tanda melawan, melainkan tanda memahami. Godwin melihat kesadaran diri dimulai saat seseorang berani mengakui: aku punya nalar, dan berhak menggunakannya.
Kesadaran ini sering datang dari momen kecil. Saat membaca berita dan merasa janggal, lalu mencari sumber lain. Saat berdiskusi dan menyadari bahwa pendapat sendiri berubah setelah mendengar argumen berbeda. Proses ini tidak nyaman, tetapi justru di sanalah kebebasan berpikir tumbuh. Kesadaran diri bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang tidak menyerahkan pikiran begitu saja.
Kebiasaan yang meninabobokan
Setelah kesadaran muncul, tantangan berikutnya adalah kebiasaan. Godwin mengingatkan bahwa kebiasaan sosial sering lebih kuat daripada paksaan. Orang bisa hidup bertahun-tahun dalam pola yang tidak disukai, hanya karena sudah terbiasa. Kebiasaan membuat sesuatu terasa normal, meski sebenarnya merugikan.
Contohnya ada di sekitar. Banyak orang terbiasa menyebut sesuatu “sudah aturan”, tanpa pernah tahu siapa yang membuat dan mengapa. Di rumah, anak jarang diajak berdiskusi karena dianggap belum pantas. Di kantor, ide segar disimpan karena takut dianggap aneh. Kebiasaan ini tidak lahir dari niat jahat, tetapi dari rasa aman semu.
Godwin melihat bahaya kebiasaan yang tidak disadari: ia mematikan refleksi. Ketika sesuatu dilakukan otomatis, nalar berhenti bekerja. Padahal kebebasan tidak pernah tumbuh dari otomatisasi hidup. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilatih sadar, seperti membiasakan membaca argumen berbeda, atau meluangkan sepuluh menit untuk berpikir ulang sebelum menyetujui sesuatu. Kebiasaan baru ini memang terasa canggung di awal, tetapi pelan-pelan menghidupkan kembali daya pikir.
Risiko menyerahkan pikiran
Jika kebiasaan patuh terus dipelihara, risikonya tidak langsung terasa, tetapi dalam jangka panjang sangat nyata. Godwin menilai bahwa menyerahkan pikiran kepada otoritas siapa pun bentuknya membuat manusia kehilangan tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ketika hasilnya buruk, yang disalahkan selalu pihak luar.
Pada kehidupan sehari-hari, ini terlihat saat orang berkata, “Saya cuma ikut perintah.” Kalimat ini terdengar netral, tetapi menyimpan bahaya. Ia memutus hubungan antara tindakan dan tanggung jawab moral. Seseorang bisa melakukan hal yang tidak ia yakini, hanya karena merasa tidak punya pilihan.
Risiko terbesar dari sikap ini adalah tumpulnya empati dan penilaian moral. Ketika nalar tidak digunakan, manusia mudah terbawa arus. Godwin khawatir bukan pada kekacauan, melainkan pada kepatuhan tanpa pikir. Masyarakat seperti ini tampak tertib, tetapi rapuh. Begitu aturan berubah atau otoritas keliru, sedikit yang mampu berdiri dengan penilaian sendiri.
Solusi melalui dialog dan nalar
Bagi Godwin, solusi tidak datang dari revolusi mendadak, melainkan dari dialog rasional yang terus-menerus. Ia percaya bahwa kebenaran lebih kuat jika lahir dari pertukaran gagasan, bukan dari paksaan. Ini terdengar sederhana, tetapi jarang dipraktikkan.
Di kehidupan nyata, dialog rasional bisa dimulai dari hal kecil. Diskusi keluarga tanpa nada menggurui. Rapat kerja yang memberi ruang berbeda pendapat tanpa sanksi sosial. Lingkungan belajar yang menghargai pertanyaan, bukan hanya jawaban cepat. Semua ini membangun kepercayaan pada nalar kolektif.
Godwin menekankan bahwa perubahan yang sehat tidak membutuhkan figur sempurna. Ia membutuhkan orang biasa yang mau berpikir jujur dan mendengarkan. Ketika dialog menjadi kebiasaan, otoritas tidak lagi berdiri di atas ketakutan, melainkan di atas persetujuan yang sadar. Inilah solusi yang tidak spektakuler, tetapi berakar kuat.
Konsistensi dalam mengelola pikiran
Kesadaran, kebiasaan, risiko, dan solusi akan sia-sia tanpa konsistensi. Godwin melihat kebebasan sebagai proses panjang, bukan tujuan instan. Menggunakan nalar sekali-dua kali tidak cukup. Ia harus dilatih seperti kebiasaan harian.
Konsistensi tampak dari pilihan kecil: tetap membaca meski lelah, tetap bertanya meski tidak populer, tetap berpikir meski hasilnya belum jelas. Seperti menyisihkan waktu lima belas menit sehari untuk refleksi, atau menunda keputusan impulsif dengan berpikir ulang. Tidak heroik, tetapi nyata.
Dengan konsistensi, seseorang tidak mudah goyah oleh tekanan sesaat. Ia tahu mengapa memilih, dan siap menanggung akibatnya. Inilah kebebasan versi Godwin: tenang, rasional, dan bertanggung jawab. Bukan bebas tanpa batas, melainkan bebas dalam mengelola diri.
Pada akhirnya, hidup tidak menunggu kondisi ideal untuk berubah. Ia bergerak ketika seseorang memutuskan menggunakan nalarnya, lalu menjaganya tetap hidup dalam kebiasaan sehari-hari. Perubahan besar lahir dari pengelolaan kecil yang konsisten.
Jika selama ini banyak keputusan diambil tanpa benar-benar dipikirkan, pertanyaannya sederhana: kapan terakhir kali nalar diberi ruang untuk memimpin, bukan sekadar mengikuti? (*)
- Penulis: Penulis
- Sumber: Logikafilsuf






















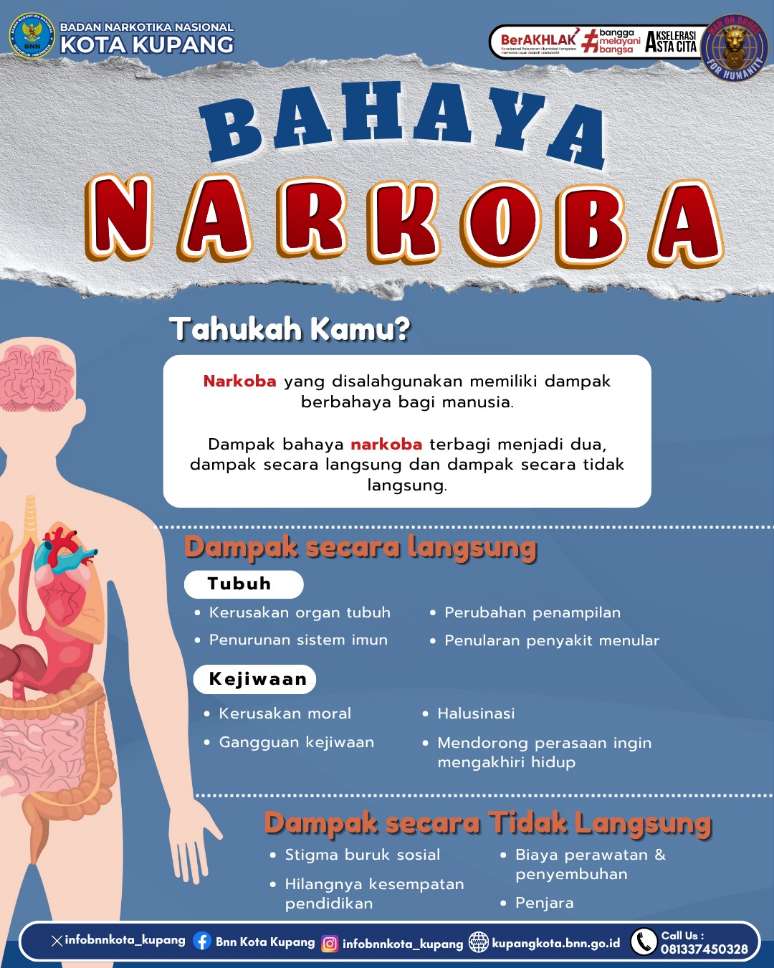






Saat ini belum ada komentar