Ridwan Kamil Mengaku Khilaf dan Minta Maaf
- account_circle Rosadi Jamani
- calendar_month Sab, 27 Des 2025
- visibility 556
- comment 0 komentar

![]()
Lelaki seperti Ridwan Kamil, tidak munafik, dan mengakui kesalahannya. Lalu, yang gentle, ia minta maaf dan mengaku khilaf.
Bangunan paling megah pun bisa runtuh bukan karena gempa besar, melainkan karena retak-retak kecil yang dibiarkan terlalu lama. Begitulah pengakuan Ridwan Kamil datang ke hadapan publik, bukan sebagai arsitek kota, bukan sebagai mantan gubernur Jawa Barat, melainkan sebagai manusia yang menyadari fondasi rumah tangganya telah ambruk perlahan. Tidak ada dentuman. Tidak ada sirene. Hanya suara lirih pengakuan, seperti beton yang patah di ruang sunyi.
Melalui Instagram, Kang Emil membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia menyampaikan permohonan maaf “dari hati yang terdalam” kepada semua pihak yang terdampak kegaduhan yang, menurutnya, tidak seharusnya terjadi. Kalimat itu seperti denah bangunan yang tiba-tiba berubah, rapi di atas kertas, tapi berantakan di lapangan. Di balik kata “kegaduhan” ada debu emosi, ada reruntuhan kepercayaan, ada ruang-ruang yang tak lagi bisa dihuni.
Ia lalu masuk ke inti paling rapuh. Pernikahan 29 tahun dengan Atalia Praratya. Dua puluh sembilan tahun adalah usia struktur yang seharusnya kokoh, fondasi dalam, kolom tegak, balok saling mengunci. Namun politisi Golkar ini memilih tidak menyalahkan cuaca, tidak menunjuk tanah, tidak menyebut beban. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengaku banyak khilaf dan dosa. Sebuah pengakuan yang terdengar sederhana, tapi bagi seorang figur publik, itu seperti merobohkan dinding penopang dengan tangan sendiri.
Dengan bahasa yang dingin sekaligus pilu, ia mengatakan, perpisahan adalah hak Atalia untuk bahagia tanpa dirinya. Kalimat ini adalah metafora arsitektur paling menyakitkan, merelakan sebuah bangunan yang ia rancang bersama, dirawat puluhan tahun, kini diserahkan kepada waktu untuk berdiri tanpa namanya tertera di plakat. Ia tidak lagi menjadi bagian dari rumah itu. Ia hanya kenangan struktural, bekas pilar yang pernah menyangga, kini tinggal jejak.
Kesedihan semakin berlapis ketika Ridwan Kamil menunduk kepada ibundanya. Di hadapan seorang ibu, semua gelar luluh. Semua proyek besar mengecil. Ia memohon ampun atas dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakan. Seperti bangunan tinggi yang akhirnya sadar, setinggi apa pun ia menjulang, akarnya tetap pada tanah paling dasar, ibu.
Yang paling memilukan, ia menyebut anak-anaknya. Anak-anak yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Mereka adalah penghuni tak bersalah dari rumah yang retak. Mereka berjalan di koridor yang tiba-tiba berubah arah, mendengar gema pertengkaran yang tak mereka rancang, merasakan dingin dari dinding yang kehilangan insulasi cinta.
Di sinilah aura pahit itu terasa. Kita hidup di negeri yang gemar memajang foto keluarga ideal di baliho, seolah rumah tangga bisa disusun serapi fasad gedung pemerintah. Kita lupa, di balik fasad, ada ruang mekanikal rumit, ada instalasi emosi yang jika salah pasang, bisa meledak perlahan. Kang Emil yang sepanjang kariernya bicara tentang tata kota dan estetika, kini berdiri di hadapan publik sebagai contoh paling getir, bahwa kehidupan tidak selalu patuh pada gambar kerja.
Ia menutup pengakuannya dengan doa, menyerahkan dirinya pada Allah, Sang Maha Pengampun. Doa itu seperti upaya terakhir memperkuat struktur yang tersisa, bukan untuk membangun ulang masa lalu, melainkan agar ia bisa berdiri sebagai bangunan baru, lebih sederhana, lebih jujur, lebih bertakwa.
Kita tidak sedang menyaksikan drama selebritas. Kita sedang melihat puing-puing kemanusiaan. Sebuah pengingat sunyi bahwa seorang arsitek paling piawai pun bisa gagal merawat rumahnya sendiri. Kesedihan tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang ia hadir sebagai retakan halus, pelan, tapi mematikan. Aura busuk bisa menjadi badai yang melumat rasa enak ubi kayu.(*)
- Penulis: Rosadi Jamani






















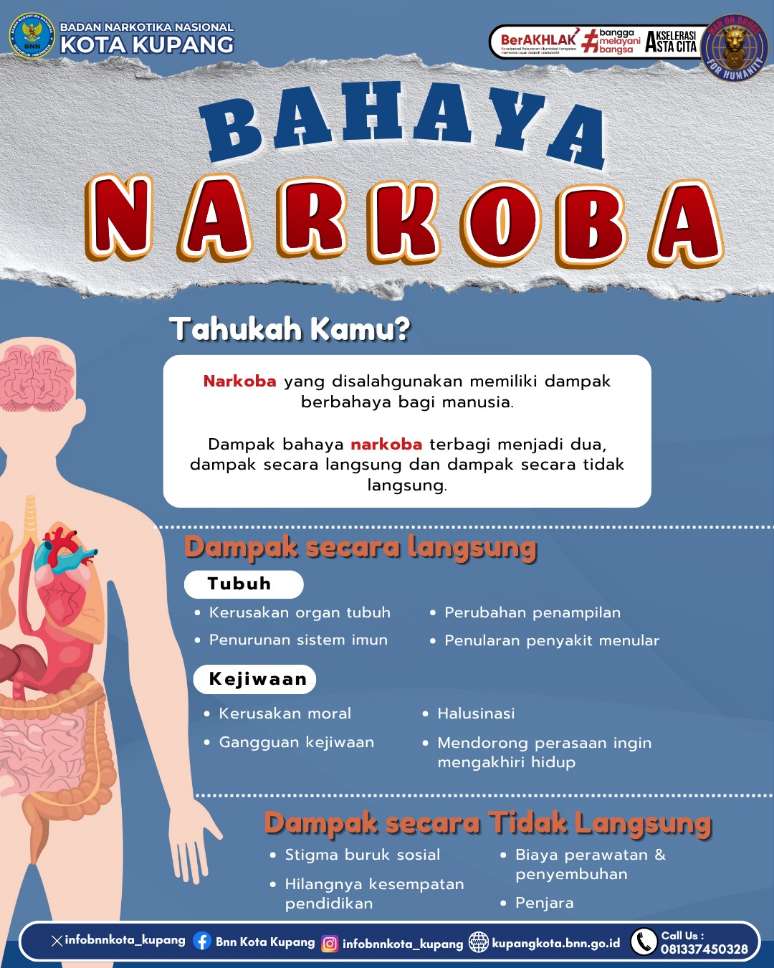






Saat ini belum ada komentar